Annelies Mellema, istri Minke, telah pergi ke Nederland. Ir. Maurits Mellema, saudara tiri Annelies, berhasil menunjukkan kuasa kulit putih atas pribumi. Ia berhasil menendang dengan sangat telak ke jantung pertahanan Minke dan Nyai Ontosoroh. Mereka menyerah dan melepas Annelies meninggalkan Hindia. Berlayar dalam kawalan maresose dan akhirnya meninggal tanpa uluran bantuan dari yang mendaku wali sah itu.
Ya, Amelia Mellema-Hammers pulang keharibaan-Nya. Annelies mati, yang otomatis mengukuhkan keahliwarisan insinyur bangunan air itu atas seluruh harta Herman Mellema di Hindia, Wonokromo.
Menurut hukum, Ir. Maurits Mellema merupakan pemilik semua yang Nyai Ontosoroh rintis dan kembangkan bersama Herman Mellema.
Begitulah, Pramoedya Ananta Toer membuka roman Anak Semua Bangsa dengan ketidakberdayaan Minke dan Nyai Ontosoroh melawan hasil keputusan Pengadilan Amsterdam. Ya, mereka kalah sekalah-kalahnya, tapi tetap tidak menyerah.
Atas dorongan semangat dari Nyai Ontosoroh, Minke berangsur sadar adanya pertentangan kolonial dengan pribumi. Pergulatan batinnya, pribumi yang feodal, bodoh dan tak berdaya berhadapan dengan kolonial Belanda yang sebaliknya dari kehidupan pribumi.
Persahabatan dengan Jean Marais dan Kommer, pelan-pelan meneguhkan kesadaran Minke. Minke mahir berbahasa Belanda, memang mengagumkan. Namun serasa kurang, ketika tak sanggup menulis Melayu.
Padahal Bahasa Melayu dimengerti dan dibaca di setiap kota besar dan kecil di seluruh Hindia. Kelemahan Minke dalam Melayu, menggugat kesadaran atas tanah air. Kecintaannya pada negeri dan bangsa sendiri. Minke, seorang pribumi terpelajar mulai menarik garis tegas: pribumi atau kolonial Belanda.
“Tahu Tuan, mereka, entah berbangsa apa, yang tidak menulis dalam bahasanya sendiri kebanyakan orang yang mencari pemuasan kebutuhan dirinya, tidak mau mengenal kebutuhan bangsa yang menghidupinya, karena kebanyakan memang tidak mengenal bangsanya sendiri?” ucap Jean Marais menuding Minke (halaman 159).
Ucapan menyakitkan yang kemudian juga dibenarkan Kommer, menantang Minke untuk lebih mengenal kehidupan pribumi. Menyakitkan karena tantangan itu berasal dari orang-orang bukan pribumi: Indo dan Perancis. Minke seorang muda dan harapan pribumi menyadari kekurangan.
Liburan ke Tulangan bersama Nyai Ontosoroh, sepenuh waktu Minke gunakan untuk mengenali nasib negerinya sendiri. Ia masuk ke pedalaman Jawa dan melihat langsung kehidupan Trunodongso, yang tinggal di tengah ladang tebu.
Melihat langsung Trunodongso, petani yang dihisap tenaga dan dirampas tanahnya, bikin Minke meradang. Betapa selama ini ia tidak benar-benar mengetahui situasi dan kondisi yang melilit negerinya.
Langsung ia mainkan pena, menulis ketidakberesan yang mendera Trunodongso. Trunodongso hendak diusir dari ladang dan sawahnya. Petani kecil yang saban hari diancam dan dimaki, tidak saja oleh Kolonial Belanda, Eropa, tapi juga menghadapi penguasa pribumi: punggawa desa, Pangreh Praja, dan para priyayi pabrik.
“Waktu orangtua sahaya masih hidup, tumpukan padi mengepung rumah kami. Ayam banyak dan itik pun banyak. Beberapa tahun sebelum orangtua sahaya meninggal, pabrik mulai mendesak sawah. Bapak sahaya menolak. Kemudian datang lurah, kemudian Ndoro Seten (asisten wedana). Bapak sahaya tetap menolak. Saluran sier (saluran tertier atau ketiga dari saluran induk) kemudian ditutup. Tak ada air lagi. Bapak sahaya....” jelas Trunodongso pada Minke (halaman 251).
Minke tulis seluruh pengalamannya bersama Trunodongso dalam bentuk cerita. Karya tulis terbaik yang mengungkap nasib pribumi, dan ia rancang untuk dimuat di koran S.N.v/d D, milik Maarten Nijman.
Namun ternyata, Minke keliru. Minke tak menduga, pemimpin redaksi itu malahan menolak karya terbaiknya. Kenapa menolak?
Ya, Minke belum sepenuhnya mengetahui hubungan tulisan terbaiknya dengan penolakan Nijman. Baru kemudian jelas setelah Kommer menerangkan keterkaitan Nijman dengan perusahaan gula. Koran Nijman merupakan koran gula, dibiayai perusahaan-perusahaan gula, dan untuk melindungi kepentingan gula.
Dan Trunodongso salah satu korban perampasan tanah dan sawah ke tangan pabrik gula. Lebih menyakitkan lagi, terutama buat Nyai Ontosoroh, ternyata mendiang suami, Herman Mellema terlibat pula dalam persekongkolan lintah darat yang menipu uang sewa tanah atas petani-petani buta huruf itu.
S.N.v/d D surat kabar gula dari semula telah berhasil memanfaatkan kepintaran menulis Minke untuk pertahankan kepentingan gula. Minke baru menyadari setelah menulis cerita nasib Trunodongso. Tulisan bernada protes terhadap ketidakadilan yang mendera beribu Trunodongso ditolak Nijman.
Ya, Trunodongso, mengingatkan saya kepada nasib warga Rembang dan Pati sekitar kawasan Kendeng yang dipaksa melepas tanah dan sawah untuk pembangunan pabrik semen. Dan, para akademis kampus, cendekiawan, budayawan, atau rohaniwan dibungkam untuk memuluskan kepentingan perusahaan semen.
Persinggungan dengan Khouw Ah Soe, pemberontak muda Tionghoa lantas menambah wawasan Minke tentang kekuasaan modal. Lebih gamblang setelah bertemu Ter Haar, rekan jurnalis asal Belanda dari golongan liberal, menyebutkan: jaman modern adalah jaman kemenangan modal.
“Biar begitu kemanusiaan tanpa pengetahuan tentang duduk soal kehidupannya sendiri, di Hindia ini, bisa tersasar. Yang dinamakan jaman modern, Tuan Tollenaar (nama pena Minke—Max Tollenaar), adalah jaman kemenangan modal. Setiap orang di jaman modern diperintah oleh modal besar, juga pendidikan yang Tuan tempuh di H.B.S. disesuaikan dengan kebutuhannya---bukan kebutuhan Tuan pribadi. Begitu juga suratkabarnya. Semua diatur oleh dia, kesusilaan, juga hukum, juga kebenaran dan pengetahuan.” (halaman 394).
Minke menggerutu, menyadari kebodohannya yang tak segera menyadari gurita kekuasaan modal. Dan “yang dikatakan modal lebih daripada hanya uang... Produksi, dagang, tetesan keringat, angkutan, hubungan, saluran---dan tak ada satu orang pun dapat bebas dari kekuasaan, pengaruh, dan perintahnya. Dan, Tuan Minke, cara berpikir, cita-cita, dibenarkan atau tidak, direstui atau tidak olehnya juga.” (halaman 395).
Akhirnya, seusai bertemu Khouw Ah Soe dan kemudian Ter Haar, Minke menahbiskan diri sebagai murid Multatuli: “Guru, hari ini aku mulai melangkah mengikuti tumitmu.”
Minke hendak berseru lewat tulisan-tulisan tentang perikemanusiaan, menolak kebiadaban, kecurangan, fitnah dan kelemahan. Minke hendak mengusung semangat Revolusi Perancis: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.
Dan lebih dari itu, menulis, baginya, adalah mengisi hidup bukan sekadar buat menyambung hidup. Menulis bukanlah untuk mendapatkan kemasyhuran dan memburu kepuasan diri semata. Apalah arti kemasyhuran, sementara orang-orang bekerja, berkeringat darah, dan bahkan tak sedikit yang mati, hanya untuk dapat makan dua kali sehari,
Nah, dari situlah saya merasakan Pramoedya Ananta Toer, melalui tokoh Minke hendak menegaskan bahwa menulis bukan hanya untuk memburu kepuasan pribadi. Menulis harus juga mengisi hidup itu sendiri. “Jean Marais bercita-cita mengisi hidup dengan lukisan-lukisannya, bukan hanya menyambung hidup.” (halaman 279).
Itulah pilihan hidup Pramoedya. Itulah wujud perlawanan Minke. Dan begitulah yang dapat saya resapi dari Anak Semua Bangsa, tetralogi Pulau Buru yang kedua: menulis itu mengisi hidup. Meski tampak kalah, tapi jelas tak menyerah.
Ungaran, 31/10/2021
Baca juga: Bumi Manusia

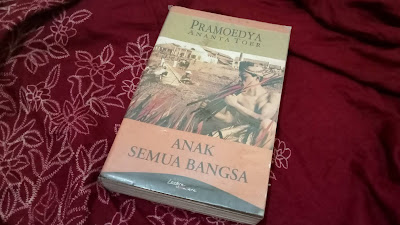







0 Comments